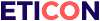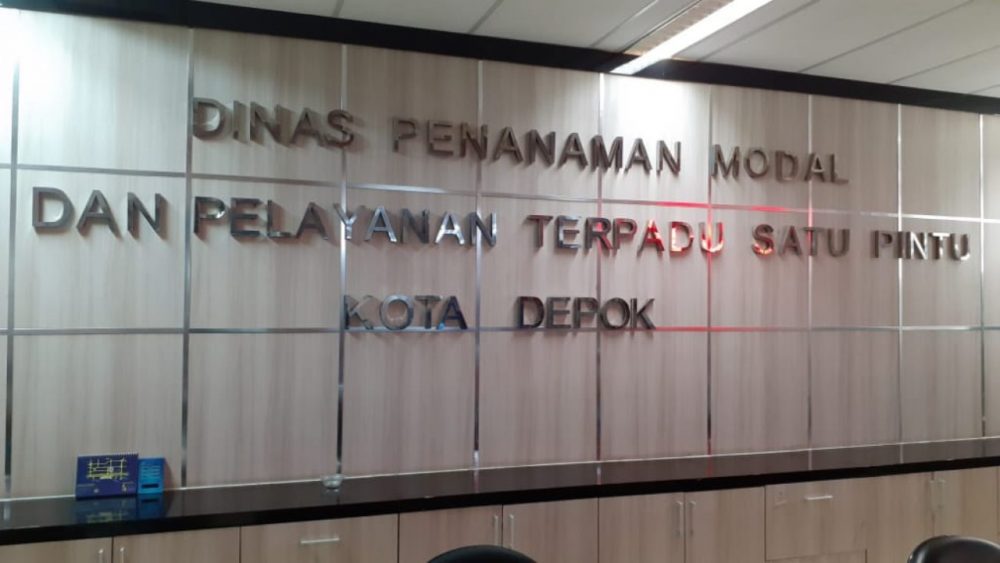APD atau Alat Pelindung Diri pada masa pandemi memang familiar digunakan oleh seseorang di bidang medis. Namun faktanya, penggunaan APD juga penting untuk pekerjaan non media di tempat kerja mereka.
Mengapa? Karena APD dibutuhkan para pekerja untuk menjaga keamanan dan keselamatan di tempat kerja yang penuh risiko.
Banyak potensi bahaya yang ada di tempat kerja, seperti kejatuhan benda berat, terluka oleh mesin produksi atau terpapar bahan kimia.
Maka pihak perusahaan perlu melakukan pengendalian untuk membantu para pekerja terhindar dari cedera, penyakit, dan potensi bahaya lainnya di tempat kerja.
Pengendalian ini bisa dengan mengontrol langsung sumber bahaya di tempat kerja. Salah satunya dengan mengajukan perizinan SILO untuk setiap peralatan yang disediakan perusahaan untuk tenaga kerja.
Tetapi pencegahan secara teknis juga tidak akan memberikan perlindungan yang cukup, diperlukan alat pelindung diri untuk mencegah segala potensi bahaya di tempat kerja.
Pedoman Penggunaan APD
Untuk memahami eksistensi penggunaan APD oleh tenaga kerja, maka perusahaan dan tenaga kerja perlu memahami pedoman dalam penggunaanya.
Berikut beberapa poin pedoman penggunaan alat perlindungan diri yang perlu diperhatikan,
Peraturan Mengenai Alat Pelindung Diri sesuai K3
Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1970, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja mereka.
Dengan kata lain penyediaan dan penggunaan APD di tempat kerja adalah salah satu bentuk implementasi keselamatan dan kesehatan kerja.
Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010, menjelaskan bahwa alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang mampu melindungi individu dengan cara menutup sebagian atau seluruh tubuh sehingga terhindar dari bahaya di tempat kerja.
Tujuan Penggunaan Alat Pelindung Diri
Tujuan penggunaan APD jika dijabarkan lebih rinci, maka bisa disimpulkan menjadi 3 poin.
Pertama, melindungi tenaga kerja dari potensi resiko bahaya K3. Kedua, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Dan ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman.
Manajemen APD
Berdasarkan pasal 7 Pemenakertrans No 8 Tahun 2010, manajemen APD meliputi
- Identifikasi kebutuhan dan syarat APD
- Memilih APD sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan tenaga kerja
- Pelatihan
- Penggunaan, perawatan, dan penyimpanan
- Pembuangan atau pemusnahan
- Pembinaan
- Inspeksi
- Evaluasi dan Pelaporan
Fungsi dan Jenis APD
Berdasarkan Pasal 3 Pemenakertrans No 8 Tahun 2010, jenis alat pelindung diri diklasifikasikan menjadi sembilan jenis, diantaranya:
- Alat Pelindung Kepala

Fungsi dari alat pelindung kepala tentunya untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan atau terpukul benda tajam yang bisa saja meluncur dari udara.
Selain itu alat pelindung kepala juga berfungsi untuk melindungi kepala dari terpapar oleh radiasi panas, api, percikan, bahan-bahan kimia, mikroorganisme dan suhu yang ekstrim.
Untuk alat pelindung kepala ini sendiri terdiri dari 3 jenis yakni helm pengaman (safety helmet), topi atau tudung kepala, dan penutup atau pengaman rambut.
- Alat Pelindung Mata dan Muka
Fungsi dari alat pelindung mata dan muka adalah melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, pancaran cahaya atau bahkan radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion.
Sama seperti alat pelindung kepala, alat pelindung mata dan muka terdiri dari beberapa alat. Diantaranya adalah kacamata pengaman, masker selam, tameng muka (face shield), dan goggles.
- Alat Pelindung Telinga
Telinga adalah salah satu bagian tubuh yang tak kalah penting untuk dilindungi. Karena terdapat banyak penyakit yang muncul akibat suara bising yang terdengar oleh telinga.
Oleh karena itu diperlukan alat pelindung telinga untuk melindungi alat pendengaran dari kebisingan atau tekanan.
Alat pelindung telinga ini seperti alat sumbat telinga (ear plug) dan penutup telinga (ear muff).
- Alat Pelindung Pernapasan
Alat pelindung pernapasan adalah alat pelindung yang berfungsi melindungi organ pernapasan dengan cara menyaring udara yang tercemar bahan kimia, mikro organisme, partikel seperti debu, kabut dan menyalurkan udara yang bersih dan sehat untuk organ pernapasan.
Jenis alat ini terdiri dari masker, respirator, katrit, kanister, airline respirator, emergency breathing apparatus dan masih banyak lagi
- Alat Pelindung Tangan
Alat ini berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, arus listrik, benturan, radiasi elektronik, pukulan dan goresan.
Alat ini terdiri dari sarung tangan yan terbuat dari logam,kulit, kain kanvas, kain atau bahan yang tahan akan bahan kimia
- Alat Pelindung Kaki

Fungsinya, untuk melindungi kaki dari terkena cairan panas atau dingin, uap panas, serta bahan kimia berbahaya.
Selain itu, pelindung kaki juga memberikan perlindungan terhadap resiko tertusuk benda tajam, tertimpa benda berat, dan tergelincir.
Terlebih jika tempat kerja yang mereka kerjakan berpotensi menimbulkan bahaya dan ledakan maka penting bagi perusahaan untuk memberikan alat pelindung kaki kepada tenaga kerja.
Alat yang termasuk dalam pelindung kaki adalah sepatu keselamatan pada pekerjaan pelebaran, konstruksi bangunan dan pengecoran logam.
- Pakaian Pelindung
Berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya paparan api dan bena panas, temperatur panas atau dingin yang ekstrim.
Di samping itu, pakaian pelindung juga mampu melindungi dari bahaya percikan bahan-bahan kimia serta benturan, tergores dan radiasi.
Terlebih radiasi sangat berpotensi untuk menyebabkan kemandulan seseorang, maka untuk mencegah hal itu terjadi penting bagi tenaga kerja untuk menggunakan pakaian pelindung.
Pakaian pelindung terdiri dari jaket, rompi dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh tubuh.
- Alat Pelindung Jatuh Perorangan
Alat ini berfungsi untuk membatasi gerak guna mencegah potensi jatuh pemakainya. Alat pelindung ini banyak digunakan pada mereka yang bekerja di tempat kerja jauh diatas permukaan tanah.
Dengan menggunakan alat ini, akan menjaga pemakainya untuk tetap berada pada posisi yang diinginkan.
Selain mencegah potensi jatuh, alat ini juga mampu menahan pemakainya sehingga tidak akan membentur lantai dasar langsung jika terjadi potensi jatuh.

Alat yang termasuk didalamnya adalah sabuk pengaman tubuh (harness), tali koneksi, tali pengaman, alat penurun, alat penjepit tali dan masih banyak lagi.
- Pelampung
Untuk mereka yang bekerja di sekitar perairan atau berada di lingkungan yang memiliki potensi tenggelam, maka pelampung wajib disediakan oleh perusahaan.
Pelampung sendiri juga memiliki kemampuan untuk mengatur keterapungan agar pengguna berada pada posisi tenggelam atau melayang didalam air.
Yang termasuk dalam pelampung adalah rompi keselamatan, jaket keselamatan, dan rompi pengatur keterapungan.
Selain menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma untuk tenaga kerja, perusahaan juga memiliki kewajiban mengumumkan secara tertulis atau memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.
Nah itulah segala pedoman penggunaan APD yang bisa kami ulas untuk Anda. Kami harap dengan artikel ini bisa meningkatkan kesadaran perusahaan dan tenaga kerja mengenai pentingnya penggunaan APD di tempat kerja.